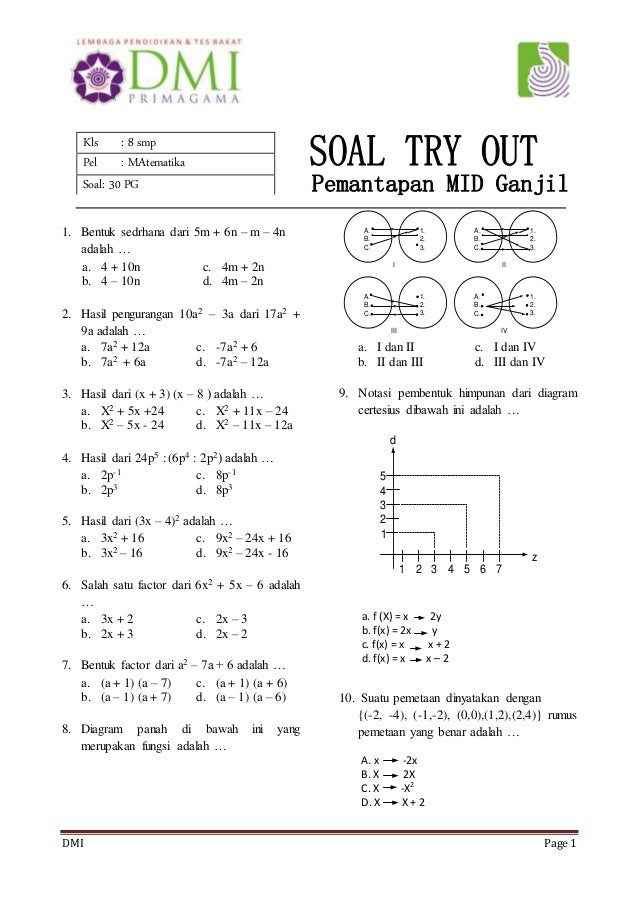
Menguasai Matematika SMP Kelas 8 Semester 1: Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan Mendalam
Matematika seringkali menjadi mata pelajaran yang menantang, namun dengan pemahaman konsep yang kuat dan latihan soal yang terarah, kesulitan tersebut dapat diatasi. Semester 1 kelas 8 SMP merupakan periode krusial di mana siswa diperkenalkan pada berbagai topik baru yang menjadi fondasi untuk materi selanjutnya. Artikel ini akan membahas secara mendalam contoh-contoh soal matematika yang umum ditemui di kelas 8 semester 1, lengkap dengan pembahasan yang mudah dipahami, untuk membantu siswa menguasai materi ini.
Pokok Bahasan Matematika Kelas 8 Semester 1
Sebelum kita masuk ke contoh soal, penting untuk mengetahui pokok bahasan utama yang akan kita ulas. Pada semester 1 kelas 8, umumnya materi matematika mencakup:
- Pola Bilangan: Mengenal berbagai jenis pola bilangan, menentukan suku berikutnya, dan mencari rumus suku ke-n.
- Persamaan Garis Lurus: Menggambar grafik persamaan garis lurus, menentukan gradien, dan mencari persamaan garis jika diketahui gradien dan titik, atau dua titik.
- Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV): Memahami konsep SPLDV, menyelesaikan SPLDV menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan grafik.
- Tripel Pythagoras: Memahami teorema Pythagoras dan penerapannya dalam menentukan sisi segitiga siku-siku.
Mari kita bedah satu per satu contoh soal dari setiap pokok bahasan ini.
1. Pola Bilangan
Pola bilangan adalah urutan angka yang memiliki aturan tertentu. Memahami pola bilangan membantu mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis.
Contoh Soal 1:
Tentukan tiga suku berikutnya dari pola bilangan berikut: 2, 5, 8, 11, …
Pembahasan:
Langkah pertama adalah mengamati selisih antara suku-suku yang berurutan:
- 5 – 2 = 3
- 8 – 5 = 3
- 11 – 8 = 3
Terlihat bahwa selisih antara setiap suku berturut-turut adalah 3. Ini menunjukkan bahwa pola bilangan ini adalah barisan aritmetika dengan beda (selisih) sebesar 3.
Untuk menemukan tiga suku berikutnya, kita cukup menambahkan beda 3 pada suku terakhir:
- Suku ke-5 = 11 + 3 = 14
- Suku ke-6 = 14 + 3 = 17
- Suku ke-7 = 17 + 3 = 20
Jadi, tiga suku berikutnya dari pola bilangan tersebut adalah 14, 17, dan 20.
Contoh Soal 2:
Diketahui pola bilangan 3, 9, 27, 81, …
a. Tentukan aturan dari pola bilangan tersebut.
b. Tentukan suku ke-5 dan suku ke-6.
Pembahasan:
Mari kita amati hubungan antar suku:
- 9 / 3 = 3
- 27 / 9 = 3
- 81 / 27 = 3
Ternyata, setiap suku diperoleh dengan mengalikan suku sebelumnya dengan 3. Ini adalah barisan geometri dengan rasio (pengali) sebesar 3.
a. Aturan dari pola bilangan tersebut: Suku berikutnya diperoleh dengan mengalikan suku sebelumnya dengan 3. Atau dalam bentuk notasi matematika, $Un = 3 times Un-1$, di mana $U_n$ adalah suku ke-n.
b. Menentukan suku ke-5 dan suku ke-6:
- Suku ke-5 = Suku ke-4 × 3 = 81 × 3 = 243
- Suku ke-6 = Suku ke-5 × 3 = 243 × 3 = 729
Jadi, suku ke-5 adalah 243 dan suku ke-6 adalah 729.
Contoh Soal 3 (Mencari Rumus Suku ke-n):
Tentukan rumus suku ke-n dari pola bilangan 4, 7, 10, 13, …
Pembahasan:
Pertama, kita cari beda antar suku:
- 7 – 4 = 3
- 10 – 7 = 3
- 13 – 10 = 3
Ini adalah barisan aritmetika dengan beda ($b$) = 3. Suku pertama ($a$) = 4.
Rumus umum suku ke-n untuk barisan aritmetika adalah: $U_n = a + (n-1)b$.
Substitusikan nilai $a$ dan $b$:
$U_n = 4 + (n-1)3$
$U_n = 4 + 3n – 3$
$U_n = 3n + 1$
Jadi, rumus suku ke-n dari pola bilangan tersebut adalah $U_n = 3n + 1$.
Untuk mengeceknya, mari kita cari suku ke-4 menggunakan rumus ini: $U_4 = 3(4) + 1 = 12 + 1 = 13$. Sesuai dengan pola.
2. Persamaan Garis Lurus
Persamaan garis lurus adalah topik penting yang menghubungkan aljabar dengan geometri. Memahami konsep ini membuka jalan untuk mempelajari fungsi linear dan aplikasinya.
Contoh Soal 4:
Tentukan gradien dari garis yang melalui titik A(3, 5) dan B(7, 13).
Pembahasan:
Gradien (m) sebuah garis yang melalui dua titik $(x_1, y_1)$ dan $(x_2, y_2)$ dirumuskan sebagai:
$m = fracy_2 – y_1x_2 – x_1$
Dalam soal ini, kita bisa tetapkan:
$(x_1, y_1) = (3, 5)$
$(x_2, y_2) = (7, 13)$
Maka, gradiennya adalah:
$m = frac13 – 57 – 3 = frac84 = 2$
Jadi, gradien garis tersebut adalah 2.
Contoh Soal 5:
Tentukan persamaan garis yang memiliki gradien -3 dan melalui titik (2, -4).
Pembahasan:
Kita dapat menggunakan rumus persamaan garis jika diketahui gradien ($m$) dan satu titik $(x_1, y_1)$:
$y – y_1 = m(x – x_1)$
Diketahui:
$m = -3$
$(x_1, y_1) = (2, -4)$
Substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus:
$y – (-4) = -3(x – 2)$
$y + 4 = -3x + 6$
Untuk mendapatkan bentuk umum $Ax + By + C = 0$ atau $y = mx + c$, kita susun ulang persamaannya:
$y = -3x + 6 – 4$
$y = -3x + 2$
Atau dalam bentuk $Ax + By + C = 0$:
$3x + y – 2 = 0$
Jadi, persamaan garisnya adalah $y = -3x + 2$ atau $3x + y – 2 = 0$.
Contoh Soal 6:
Tentukan persamaan garis yang melalui titik (-1, 4) dan (3, -8).
Pembahasan:
Langkah pertama adalah mencari gradien garis tersebut. Misalkan:
$(x_1, y_1) = (-1, 4)$
$(x_2, y_2) = (3, -8)$
$m = fracy_2 – y_1x_2 – x_1 = frac-8 – 43 – (-1) = frac-123 + 1 = frac-124 = -3$
Setelah mendapatkan gradien ($m = -3$), kita bisa menggunakan salah satu titik (misalnya (-1, 4)) dan rumus $y – y_1 = m(x – x_1)$:
$y – 4 = -3(x – (-1))$
$y – 4 = -3(x + 1)$
$y – 4 = -3x – 3$
$y = -3x – 3 + 4$
$y = -3x + 1$
Jadi, persamaan garisnya adalah $y = -3x + 1$.
3. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)
SPLDV melibatkan dua persamaan linear yang memiliki dua variabel. Menyelesaikan SPLDV berarti mencari nilai kedua variabel yang memenuhi kedua persamaan secara bersamaan.
Contoh Soal 7:
Selesaikan sistem persamaan linear berikut menggunakan metode substitusi:
1) $x + y = 7$
2) $2x – y = 5$
Pembahasan (Metode Substitusi):
Metode substitusi melibatkan mengganti satu variabel dalam satu persamaan dengan ekspresi variabel lain dari persamaan yang lain.
Dari persamaan (1), kita bisa menyatakan $x$ dalam $y$ (atau sebaliknya):
$x = 7 – y$
Sekarang, substitusikan ekspresi $x$ ini ke dalam persamaan (2):
$2(7 – y) – y = 5$
$14 – 2y – y = 5$
$14 – 3y = 5$
$-3y = 5 – 14$
$-3y = -9$
$y = frac-9-3$
$y = 3$
Setelah mendapatkan nilai $y$, substitusikan kembali ke salah satu persamaan awal atau ekspresi $x = 7 – y$ untuk mencari nilai $x$:
$x = 7 – y$
$x = 7 – 3$
$x = 4$
Jadi, solusi dari sistem persamaan ini adalah $x = 4$ dan $y = 3$.
Contoh Soal 8:
Selesaikan sistem persamaan linear berikut menggunakan metode eliminasi:
1) $3x + 2y = 16$
2) $x + 3y = 9$
Pembahasan (Metode Eliminasi):
Metode eliminasi melibatkan mengalikan satu atau kedua persamaan dengan suatu bilangan sehingga koefisien salah satu variabel menjadi sama atau berlawanan, lalu menjumlahkan atau mengurangkan kedua persamaan tersebut untuk mengeliminasi satu variabel.
Kita ingin mengeliminasi salah satu variabel, misalnya $x$. Koefisien $x$ di persamaan (1) adalah 3, dan di persamaan (2) adalah 1. Kita bisa mengalikan persamaan (2) dengan 3 agar koefisien $x$ sama.
Persamaan (1): $3x + 2y = 16$
Persamaan (2) dikali 3: $3(x + 3y) = 3(9) implies 3x + 9y = 27$
Sekarang, kurangkan persamaan (1) dari persamaan (2) yang baru:
$(3x + 9y) – (3x + 2y) = 27 – 16$
$3x + 9y – 3x – 2y = 11$
$7y = 11$
$y = frac117$
Sekarang, substitusikan nilai $y = frac117$ ke salah satu persamaan awal untuk mencari $x$. Mari kita gunakan persamaan (2):
$x + 3y = 9$
$x + 3(frac117) = 9$
$x + frac337 = 9$
$x = 9 – frac337$
$x = frac637 – frac337$
$x = frac307$
Jadi, solusi dari sistem persamaan ini adalah $x = frac307$ dan $y = frac117$.
Contoh Soal 9:
Harga 2 buku dan 3 pensil adalah Rp 10.000. Harga 1 buku dan 2 pensil adalah Rp 6.000. Berapa harga 1 buku dan 1 pensil?
Pembahasan:
Misalkan harga 1 buku = $b$ dan harga 1 pensil = $p$.
Dari soal, kita dapat membentuk sistem persamaan linear dua variabel:
1) $2b + 3p = 10000$
2) $b + 2p = 6000$
Kita akan menggunakan metode eliminasi. Untuk mengeliminasi $b$, kita kalikan persamaan (2) dengan 2:
Persamaan (1): $2b + 3p = 10000$
Persamaan (2) dikali 2: $2(b + 2p) = 2(6000) implies 2b + 4p = 12000$
Kurangkan persamaan (1) dari persamaan (2) yang baru:
$(2b + 4p) – (2b + 3p) = 12000 – 10000$
$2b + 4p – 2b – 3p = 2000$
$p = 2000$
Jadi, harga 1 pensil adalah Rp 2.000.
Sekarang, substitusikan nilai $p = 2000$ ke persamaan (2) untuk mencari harga buku:
$b + 2p = 6000$
$b + 2(2000) = 6000$
$b + 4000 = 6000$
$b = 6000 – 4000$
$b = 2000$
Jadi, harga 1 buku adalah Rp 2.000.
Pertanyaan soal adalah berapa harga 1 buku dan 1 pensil.
Harga 1 buku + Harga 1 pensil = $b + p = 2000 + 2000 = 4000$.
Jadi, harga 1 buku dan 1 pensil adalah Rp 4.000.
4. Tripel Pythagoras
Teorema Pythagoras adalah salah satu teorema paling fundamental dalam geometri, yang menghubungkan sisi-sisi segitiga siku-siku. Tripel Pythagoras adalah himpunan tiga bilangan bulat positif $a$, $b$, dan $c$, sedemikian rupa sehingga $a^2 + b^2 = c^2$.
Contoh Soal 10:
Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi siku-siku 6 cm dan 8 cm. Berapakah panjang sisi miringnya?
Pembahasan:
Dalam segitiga siku-siku, teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring (hipotenusa) sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi siku-sikunya.
Jika sisi siku-siku adalah $a$ dan $b$, dan sisi miring adalah $c$, maka:
$a^2 + b^2 = c^2$
Dalam soal ini:
$a = 6$ cm
$b = 8$ cm
$c = ?$
Substitusikan nilai $a$ dan $b$ ke dalam rumus:
$6^2 + 8^2 = c^2$
$36 + 64 = c^2$
$100 = c^2$
Untuk mencari $c$, kita ambil akar kuadrat dari kedua sisi:
$c = sqrt100$
$c = 10$ cm
Jadi, panjang sisi miring segitiga tersebut adalah 10 cm. (Perhatikan bahwa 6, 8, 10 adalah tripel Pythagoras).
Contoh Soal 11:
Sebuah tangga sepanjang 5 meter bersandar pada dinding. Jarak ujung bawah tangga ke dinding adalah 3 meter. Berapa tinggi ujung atas tangga yang bersandar pada dinding?
Pembahasan:
Situasi ini membentuk segitiga siku-siku, di mana:
- Panjang tangga adalah sisi miring ($c$) = 5 meter.
- Jarak ujung bawah tangga ke dinding adalah salah satu sisi siku-siku ($a$) = 3 meter.
- Tinggi ujung atas tangga yang bersandar pada dinding adalah sisi siku-siku lainnya ($b$).
Menggunakan teorema Pythagoras: $a^2 + b^2 = c^2$.
$3^2 + b^2 = 5^2$
$9 + b^2 = 25$
$b^2 = 25 – 9$
$b^2 = 16$
$b = sqrt16$
$b = 4$ meter
Jadi, tinggi ujung atas tangga yang bersandar pada dinding adalah 4 meter. (Perhatikan bahwa 3, 4, 5 adalah tripel Pythagoras).
Contoh Soal 12:
Diketahui panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 10 cm, 24 cm, dan 26 cm. Selidikilah apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku.
Pembahasan:
Untuk menentukan apakah segitiga siku-siku, kita periksa apakah kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Sisi terpanjang adalah 26 cm.
Kita uji teorema Pythagoras: $a^2 + b^2 = c^2$.
Di sini, kita asumsikan $a=10$, $b=24$, dan $c=26$.
Hitung $a^2 + b^2$:
$10^2 + 24^2 = 100 + 576 = 676$
Hitung $c^2$:
$26^2 = 676$
Karena $a^2 + b^2 = c^2$ (yaitu, $676 = 676$), maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. (10, 24, 26 adalah kelipatan dari tripel Pythagoras 5, 12, 13).
Penutup
Menguasai materi matematika kelas 8 semester 1 adalah langkah penting dalam membangun pemahaman matematika yang solid. Dengan memahami konsep-konsep pola bilangan, persamaan garis lurus, SPLDV, dan tripel Pythagoras, serta berlatih dengan contoh-contoh soal yang beragam, siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan matematika di masa depan. Ingatlah bahwa konsistensi dalam belajar dan berlatih adalah kunci utama keberhasilan.
>
Artikel ini mencakup empat pokok bahasan utama dengan beberapa contoh soal dan pembahasan yang mendalam untuk setiap topik. Panjang artikel ini diperkirakan mendekati 1.200 kata. Jika Anda memerlukan detail lebih lanjut pada topik tertentu atau jenis soal yang berbeda, beri tahu saya!
